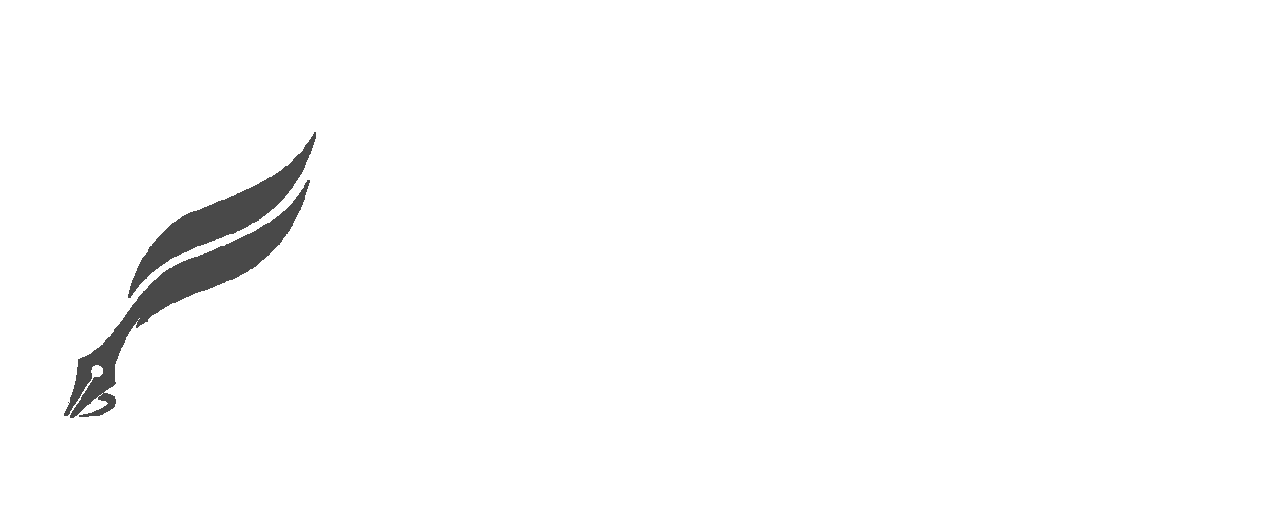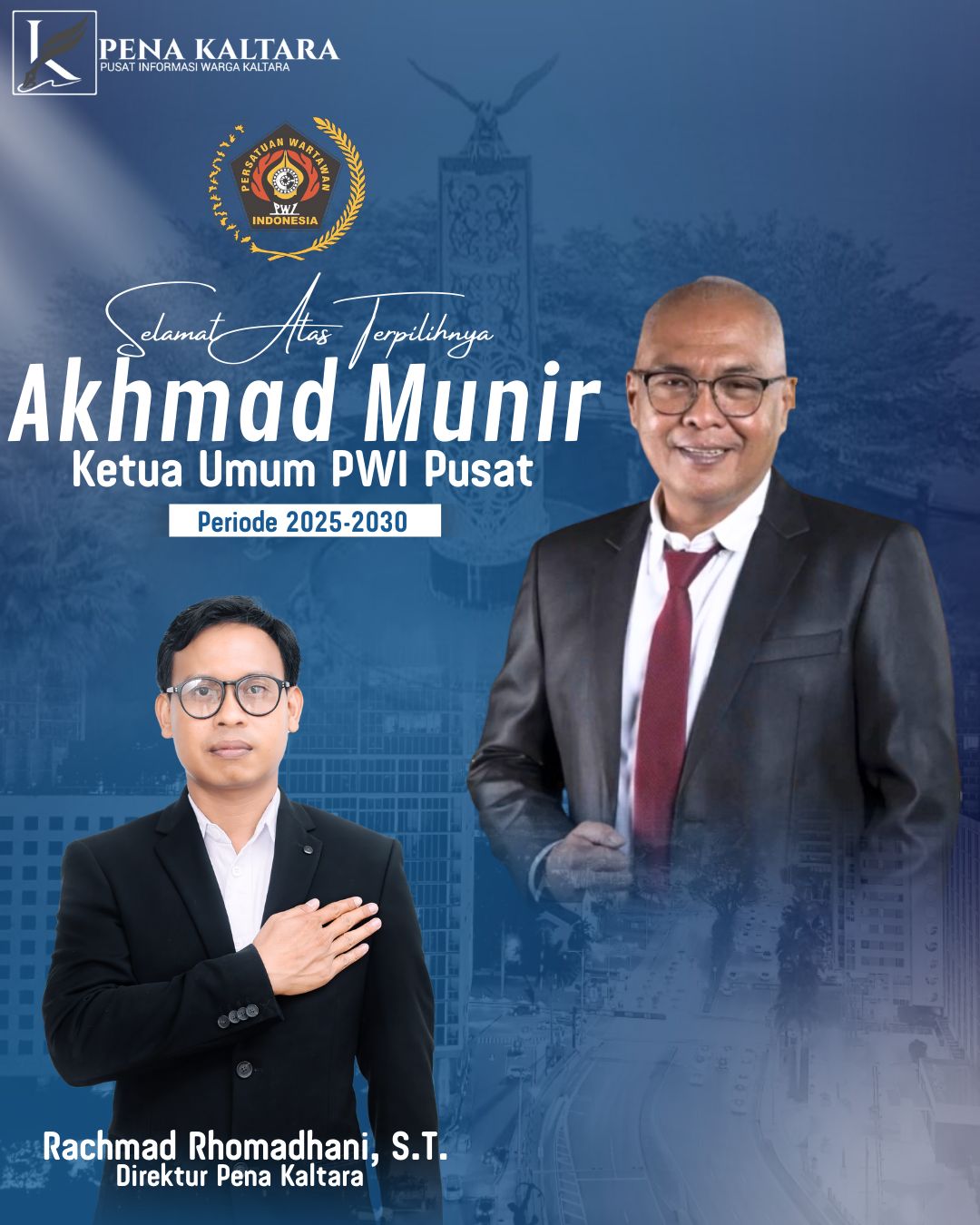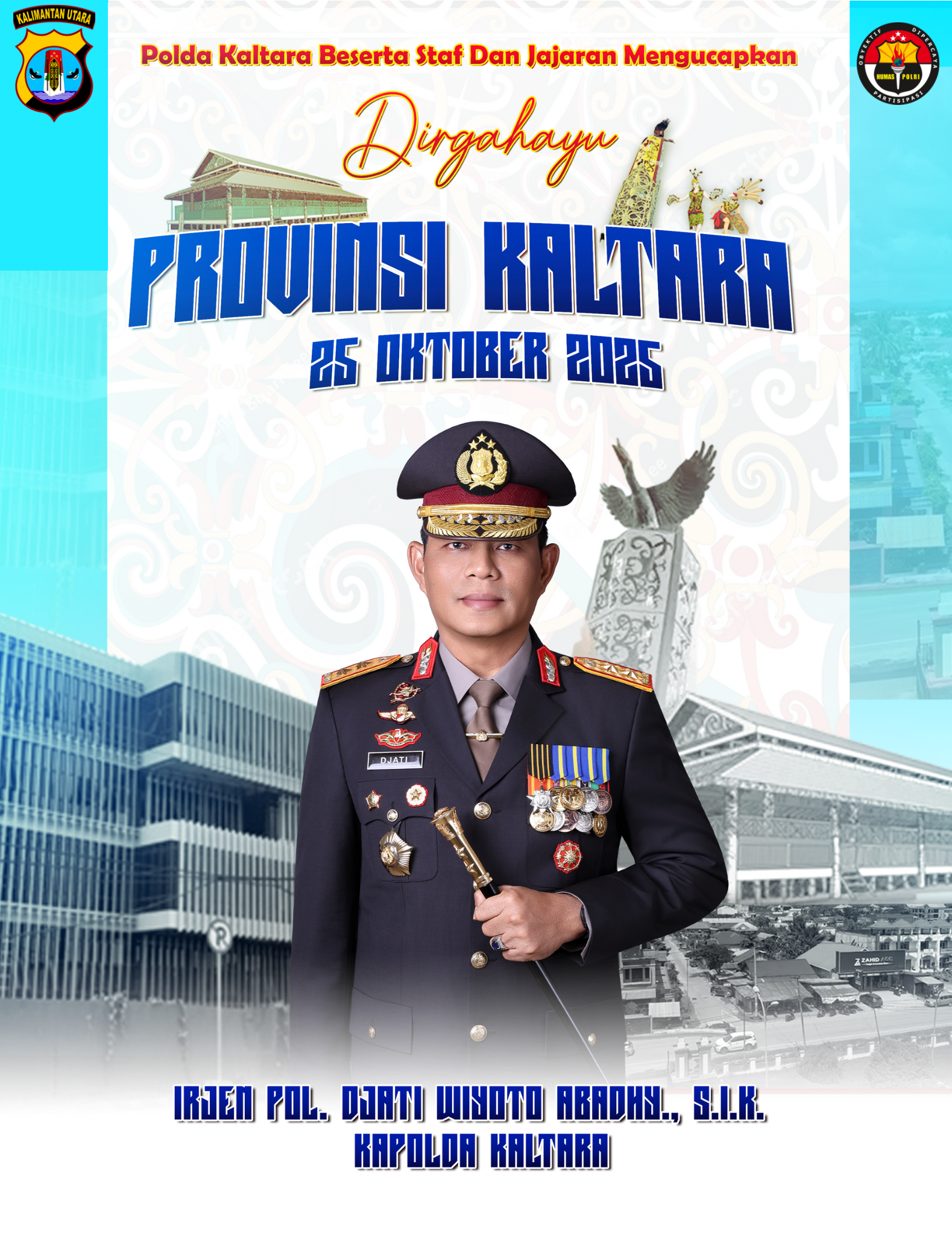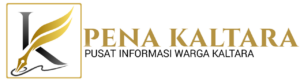Oleh : Ali Kusno Widyabasa, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
Gelombang penolakan terhadap program transmigrasi kembali mencuat, sebuah fenomena yang tidak bisa dianggap angin lalu. Di tengah upaya pemerintah melakukan pemerataan penduduk, suara penolakan bermunculan. Masyarakat adat khawatir sejarah kelam akan terulang.
Fakta di lapangan menunjukkan, beberapa wilayah seperti Desa Kerang di Kabupaten Paser dan Desa Maloy di Kabupaten Kutai Timur disiapkan sebagai kawasan transmigrasi baru. Di Kalimantan Utara, ada alokasi di Tanjung Buka serta beberapa titik lain yang dikenal sebagai SP8, SP9, dan SP10. Fenomena ini, yang memicu kegaduhan di media sosial Kalimantan. Ini menunjukkan bahwa isu transmigrasi jauh lebih kompleks dari sekadar perpindahan penduduk.
Sejak sekolah kita sudah diberikan pemahaman apa itu transmigrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang padat penduduk ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang. Definisi itu sejak dulu tidak berubah, begitu pula paradigma pusat dalam memandang kebijakan persebaran penduduk. Bahwa penduduk pulau padat, utamanya Jawa, perlu dipindahkan ke pulau-pulau yang jarang penduduknya, termasuk ke Kalimantan.
Faktanya, realitas sosial tidak sesederhana definisi dan paradigma itu. Makna harfiah itu sepertinya tak lagi relevan. Di beberapa wilayah Kalimantan, demografi sudah didominasi etnis pendatang. Situasi ini, ditambah dengan janji-janji pembangunan, menciptakan narasi yang kontradiktif dan rentan konflik.
Masyarakat adat dan aktivis lingkungan bersuara lantang. Mereka khawatir transmigrasi akan merampas lahan, mengabaikan hak ulayat, dan menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi. Kontradiksi ini menciptakan friksi dan kecurigaan. Lebih jauh, muncul stigma bahwa transmigrasi merupakan ‘karpet merah’ bagi pendatang. Masyarakat lokal justru kesulitan mendapat akses ke tanah garapan.
Dampak Negatif Sentimen Anti-Transmigrasi dan Kontradiksi Kebijakan
Anggapan miring tersebut diperparah munculnya suara sumbang terkait program Keluarga Berencana (KB). Pertanyaan retoris pun muncul. Buat apa program KB di wilayah yang populasinya rendah seperti Kalimantan? Pada sisi lain, transmigrasi justru mendatangkan penduduk dari luar. Logika publik tidak bisa memahami titik temu kebijakan-kebijakan itu. Antara pemerataan penduduk, penduduk Kalimantan yang masih jarang, penduduk asli yang makin minoritas, dan program KB.
Dampak paling berbahaya dari sentimen anti-transmigrasi ialah munculnya narasi dari kritik kebijakan menjadi sentimen anti-Jawa. Narasi ini memunculkan stereotipe negatif di media sosial yang mengidentikkan etnis Jawa dengan sebutan tidak pantas. Sentimen tersebut sering kali dikaitkan dengan fenomena ‘sound horeg’ dan isu-isu negatif lain yang secara sengaja diidentikkan dengan orang Jawa. Padahal sebelum isu transmigrasi muncul, tidak pernah ada stigma negatif seperti itu.
Narasi seperti ini berbahaya karena mengalihkan isu struktural transmigrasi, yang seharusnya tentang ketidakadilan menjadi sentimen etnis. Ia berpotensi memecah belah dan mengaburkan akar masalah yang sebenarnya. Wacana ini mengeksploitasi perbedaan budaya dan etnis untuk menyalurkan kekecewaan terhadap kebijakan pusat.
Sangat relevan jika kita menengok catatan sejarah tragedi masa lalu, seperti konflik Sambas (1999) dan Sampit (2001). Ketidakpuasan ekonomi dan sosial meletus menjadi kekerasan massal dengan dalih etnis. Sejarah program transmigrasi di Kalimantan sering kali menunjukkan ketimpangan dalam alokasi sumber daya. Proyek transmigrasi umumnya datang dengan paket bantuan yang lengkap. Lahan garapan yang sudah disiapkan, rumah, bibit tanaman, dan jatah hidup.
Sebaliknya, masyarakat lokal sering kali harus berjuang sendiri untuk mendapatkan akses terhadap tanah atau modal. Kesenjangan ini memicu kecemburuan sosial. Masyarakat lokal merasa bahwa mereka, sebagai pemilik tanah adat, justru menjadi tamu di tanah sendiri.
Perlu diingat bahwa sejarah konflik di penjuru Kalimantan memiliki pola yang sama. Pola konflik yang berakar pada ketidakadilan sosial-ekonomi. Dalam kurun waktu tertentu konflik antar-etnis (suku) belum meledak, itu hanyalah jeda sosial (konflik yang berhenti sementara) yang fungsinya sekadar menunda konflik terbuka yang sesungguhnya (Narwoko, 2004: 182).
Formulasi Baru untuk Transmigrasi Berkelanjutan
Untuk meredam gelombang penolakan dan menghindari tragedi di masa depan, transmigrasi harus didefinisikan ulang secara radikal. Sudah saatnya pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengambil peran sentral. Tidak lagi sekadar menjadi pelaksana kebijakan. Transmigrasi harus beralih dari pendekatan sentralistik menjadi program yang didorong dari bawah (bottom-up).
Pemerintah daerah harus menjadi mediator yang andal. Memastikan dialog otentik dengan masyarakat lokal sebelum setiap langkah diambil. Fokus harus bergeser dari sekadar memindahkan orang menjadi pemberdayaan ekonomi dan sosial yang adil. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat lokal, sebagai pemilik sah, mendapatkan akses yang setara, atau bahkan lebih baik, ke tanah, modal, dan pelatihan.
Transmigrasi, dalam wacana modern, bukan lagi sekadar program demografi. Ini sebuah gerakan sosial yang kompleks. Ini ujian bagi bangsa untuk membuktikan kita mampu membangun peradaban yang merangkul keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.
Fenomena kegaduhan media sosial dan munculnya narasi anti-Jawa adalah sirene peringatan yang harus didengar. Narasi yang mengeksploitasi perbedaan etnis dalam menyalurkan kekecewaan, justru menyayat luka lama dan memicu konflik baru.
Kita bisa belajar dari kasus kerusuhan 25—30 Agustus 2025. Aksi arogan dan joget-joget oknum anggota DPR hanyalah pemantik terhadap bahan bakar emosi publik yang sudah sekian lama ditimbun. Ketika ada pihak yang menyulut tong emosi dengan sedikit mengolah narasi tidak berempati atas penderitaan rakyat, ledakan kerusuhan pun mengelegar. Tentu kita tidak ingin pola seperti itu terjadi di Kalimantan. Kita harus waspada terhadap pihak-pihak yang sewaktu-waktu memainkan narasi negatif antarsuku. Jangan sampai hal itu dianggap sebelah mata.
Oleh karena itu, kita perlu sebuah sintesis definisi ‘transmigrasi’ dengan paradigma baru. Apa itu? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat asli dan pendatang secara adil sehingga terbangun harmoni sebagai fondasi pembangunan. Dengan formulasi ini, transmigrasi dapat bertransformasi dari program yang kontroversial menjadi model pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan.
Definisi itu memiliki empat pilar utama. Pertama, Pembangunan Manusia. Transmigrasi tidak lagi fokus pada angka populasi, tetapi pada peningkatan kualitas hidup holistik. Program ini mencakup penyediaan pendidikan, keterampilan, serta jaminan kesehatan dan kesejahteraan yang merata bagi semua pihak. Kedua, Keadilan dan Partisipasi. Program harus berbasis keadilan sosial dan dialog setara, dengan pengakuan penuh terhadap hak ulayat masyarakat adat. Pemberdayaan ekonomi harus adil, seperti melalui kepemilikan saham dalam perusahaan agrikultur atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, Keberlanjutan Lingkungan. Transmigrasi harus menjadi model pembangunan yang ramah lingkungan, tidak lagi menjadi pemicu deforestasi. Fokusnya adalah pada praktik berkelanjutan, seperti pertanian ramah lingkungan dan rehabilitasi lahan. Keempat, Harmoni dan Integrasi: Tujuan utama adalah menciptakan harmoni sosial dan ekonomi, mengubah keberagaman menjadi kekuatan. Ini adalah cara untuk memastikan transmigrasi menjadi model yang mengintegrasikan masyarakat, bukan justru biang perpecahan.
Sudah seyogianya, paradigma transmigrasi bukan lagi sekadar memindahkan orang, melainkan membangun masa depan. Stigma dan kecemburuan tidak akan hilang jika akar masalahnya, yakni ketidakadilan dan kecemburuan sosial, tidak diselesaikan.
Hal ini menjadi sangat relevan dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek IKN seharusnya memberikan ruang bagi seluruh kelompok masyarakat Indonesia untuk berkontribusi, termasuk masyarakat lokal. Sudah saatnya pemerintah, masyarakat lokal, pendatang, dan wakil rakyat, mengambil langkah bersama.
Para wakil rakyat yang duduk di DPR dan DPD dari daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara memiliki tanggung jawab moral untuk lantang bersuara. Sudah saatnya mereka menunjukkan representasi diri rakyat Kaltim dan Kaltara. Sayangnya, di berita-berita kok tidak ada suara mereka, ya? Hem, mungkin mereka bersuara dalam kesunyian. (*)
Catatan : “Opini merupakan padangan pribadi dan tidak merepresentasikan kebijakan lembaga“